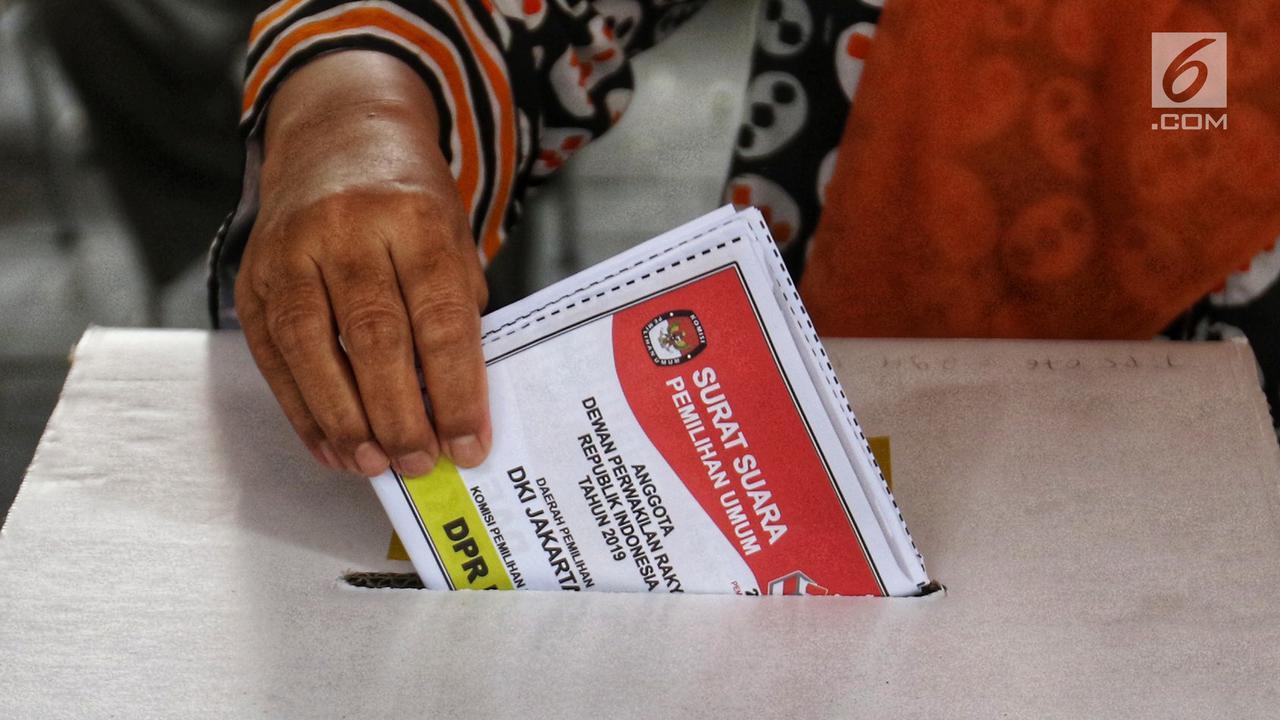Teheran, dini hari. Langit belum sepenuhnya terang ketika dentuman datang dari arah utara kota. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan. Hanya keheningan yang dipecah tiba-tiba oleh ledakan.
Dan dalam hitungan menit, dunia berubah.
Tiga tokoh militer penting Iran—Jenderal Hossein Salami, Mohammad Bagheri, dan Amir Ali Hajizadeh—tewas dalam serangan udara. Serangan yang disebut-sebut sebagai langkah “pencegahan” dari Israel atas ancaman nuklir Iran. Tapi di balik istilah yang terdengar strategis itu, nyawa tetaplah nyawa.
Bersama mereka, lebih dari 50 warga sipil ikut jadi korban. Tak berseragam, tak berdiri di garis depan. Mereka hanya kebetulan tinggal di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Anak-anak yang masih tertidur, orang tua yang baru saja menyeduh teh pagi. Semua disapu oleh sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan.
Dunia langsung bergerak. Iran menyebut ini deklarasi perang. Israel bilang ini soal keamanan nasional. Media berebut headline. Analis politik duduk di studio, berbicara soal “eskalasi” dan “respons militer.”
Tapi siapa yang bicara untuk seorang ibu yang kehilangan anaknya di tengah puing rumah? Siapa yang menjelaskan pada anak kecil kenapa ayahnya tidak akan pulang?
Mereka yang tertinggal tak butuh pernyataan resmi. Mereka butuh ketenangan, kejelasan, dan yang paling sulit: alasan.
Kota Teheran hari itu seperti terbelah. Separuh marah, separuh berduka. Antara dendam dan kehilangan. Antara ingin melawan, dan hanya ingin pulih. Dan di tengahnya, ada orang-orang yang hanya ingin hidup. Biasa saja. Bangun pagi, kerja, pulang, bertemu keluarga. Tapi itu pun sekarang terasa mewah.
Kita, yang duduk jauh dari medan peristiwa, mudah sekali bicara tentang geopolitik. Tapi mungkin sesekali kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menganalisis—tapi untuk berempati.
Karena satu hal yang selalu benar: di setiap konflik berskala besar, korban pertamanya adalah orang-orang kecil yang tidak pernah minta ikut perang.